
Aceh: Dari Kejayaan Masa Lalu ke Tantangan Pembangunan Kini
Aceh, sebuah wilayah yang kaya akan sejarah dan budaya, memiliki identitas unik yang terpahat dalam tinta emas sejarah Indonesia. Sebagai pintu gerbang penyebaran Islam dan kerajaan-kerajaan besar yang pernah jaya, Aceh telah menjadi pusat peradaban dan perdagangan internasional sebelum minyak dan gas bumi ditemukan. Kesultanan Aceh Darussalam di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda adalah kekuatan politik dan ekonomi yang disegani di kawasan.
Kesejahteraan masyarakat pada masa itu dibangun di atas fondasi kedaulatan maritim, keunggulan komoditas perdagangan seperti lada, serta sistem pemerintahan yang terintegrasi dengan nilai-nilai Islam. Syariat Islam bukan sekadar simbol, tetapi menjadi ruh dalam tata kelola pemerintahan dan kehidupan sosial-ekonomi, mendorong kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial.
Namun, konflik dan bencana tsunami 2004 menghancurkan fondasi sosial-ekonomi Aceh. Meski rekonsiliasi dan rehabilitasi pasca-tsunami berjalan dengan dukungan internasional yang masif, trauma kolektif meninggalkan luka yang dalam pada struktur perekonomian dan tata kelola pemerintahan.
Tantangan Pembangunan Saat Ini
Pasca perdamaian dan otonomi khusus, Aceh memasuki babak baru. Dana otonomi khusus dan bagi hasil migas mengalir deras ke kas daerah. Sayangnya, kelimpahan dana ini tidak serta-merta mentransformasi kesejahteraan masyarakat secara signifikan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh per Maret 2024 menunjukkan tingkat kemiskinan masih berada di angka 14,99 persen, tertinggi ketiga di Sumatera dan jauh di atas rata-rata nasional yang sekitar 9,36 %. Angka pengangguran terbuka (TPT) Aceh juga konsisten berada di peringkat atas nasional, berkisar di 6-7 %, mengindikasikan lemahnya penyerapan tenaga kerja.
Ini adalah "penyakit ekonomi" yang merugiakan. Pengangguran yang tinggi tidak hanya menjadi beban sosial, tetapi juga memicu lingkaran setan kemiskinan dan berpotensi meningkatkan ketimpangan (Gini Ratio). Yang memprihatinkan, kekayaan alam Aceh yang luar biasa, terutama dari sektor migas, belum sepenuhnya menjadi mesin penggerak ekonomi kerakyatan. Ekonomi masih bertumpu pada sektor konsumtif dan belanja pemerintah, sementara sektor riil seperti pertanian, perikanan, dan industri pengolahan belum bangkit secara optimal.
Di tengah tantangan ini, penerapan syariat Islam sebagai pedoman hidup masyarakat Aceh seringkali hanya terlihat pada aspek simbolis dan hukumatif (qanun), seperti pada persoalan busana dan khalwat. Esensi syariat Islam yang sejatinya menekankan keadilan, pemberantasan korupsi, pemenuhan kebutuhan dasar (al-dharuriyat al-khams), dan pengelolaan harta umat (Baitul Mal) untuk kesejahteraan bersama, belum menjadi arus utama dalam perencanaan pembangunan.
Langkah Menuju Masa Depan yang Lebih Sejahtera
Lantas, bagaimana memutus mata rantai kemiskinan ini? Aceh membutuhkan terobosan dan "tritmen khusus" yang masif dan terarah. Syariat Islam harus dihadirkan bukan hanya sebagai norma hukum, tetapi sebagai paradigma pembangunan. Prinsip-prinsip maqashid syariah (tujuan syariah) yang melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, harus diterjemahkan ke dalam indikator pembangunan yang konkret.
Pertama, mengubah mindset penyusunan anggaran. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus diminta pertanggungjawabannya bukan hanya pada penyerapan anggaran, tetapi pada outcome yang dicapai. Setiap OPD harus memiliki program terukur dengan target spesifik, misalnya "menurunkan kemiskinan sebesar 5% dalam setahun di wilayah kerjanya."
Kedua, mendesain program yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Dana APBA yang besar harus dialihkan secara signifikan untuk program-program yang membuka lapangan kerja dan memberdayakan masyarakat miskin. Beberapa fokus yang dapat dilakukan:
- Revolusi Pertanian dan Perikanan: Aceh memiliki potensi pertanian dan perikanan yang luar biasa. Program bukan hanya tentang bagi-bagi bibit, tetapi membangun ekosistem dari hulu ke hilir: perbaikan irigasi, akses permodalan syariah (melalui Baitul Mal), teknologi pascapanen, dan yang terpenting, pemasaran.
- Membangun industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan akan menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja.
- Pemberdayaan UMKM Berbasis Syariah: UMKM adalah penyerap tenaga kerja terbesar. Pemerintah harus aktif membina, mempertemukan dengan pasar, dan memberikan akses pembiayaan melalui skim-skim syariah yang adil dan tidak memberatkan.
- Pelatihan kewirausahaan yang mengintegrasikan etika bisnis Islam harus digencarkan.
Ketiga, memperkuat peran Baitul Mal. Lembaga ini jangan hanya fokus pada zakat fitrah dan pengelolaan kuburan. Baitul Mal Aceh harus dioptimalkan sebagai lembaga keuangan syariah sosial yang powerful untuk penanggulangan kemiskinan. Dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) yang terkumpul harus dikelola secara profesional untuk program pemberdayaan produktif, beasiswa pendidikan, dan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin.
Perjalanan panjang Aceh dari masa kejayaan, melalui lembah konflik dan bencana, hingga kini berdiri dengan otonomi khusus, adalah sebuah modal sosial yang tak ternilai. Kini, saatnya Aceh bangkit dengan caranya sendiri. Syariat Islam yang menjadi identitas, harus menjadi kekuatan moral dan etika dalam membangun peradaban yang sejahtera.
Dengan komitmen politik yang kuat, tata kelola anggaran yang berorientasi pada hasil, dan program pemberdayaan yang masif, target menurunkan kemiskinan 5 % per tahun bukanlah hal yang mustahil. Masa depan Aceh terletak pada kemampuannya menyelaraskan kemuliaan syariat dengan kesejahteraan ekonomi, membuktikan kepada dunia bahwa di bumi Serambi Mekkah ini, iman dan kemakmuran dapat berjalan beriringan.
Aceh harus kembali menjadi mercusuar, bukan hanya dalam keteguhan syariat, tetapi juga dalam pencapaian pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.












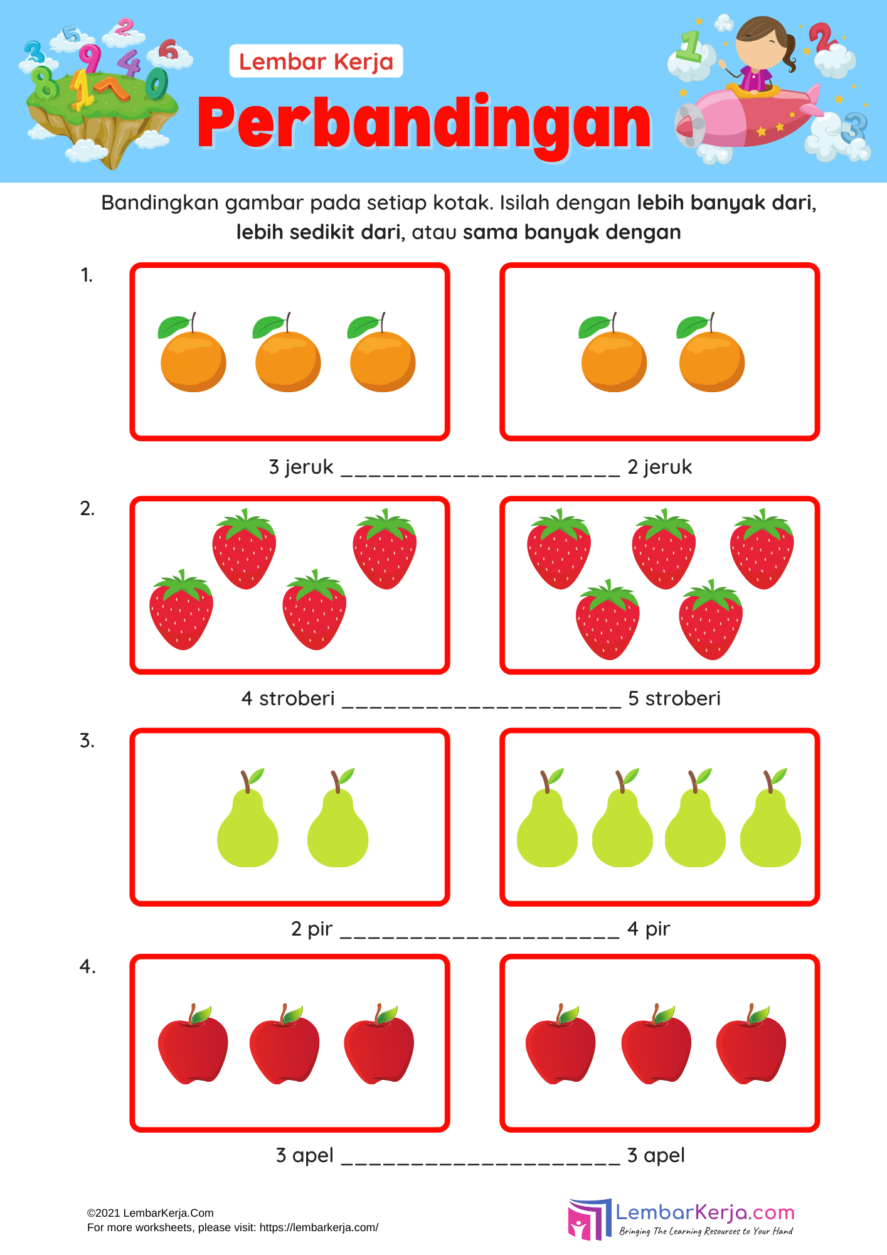

Komentar
Kirim Komentar