 Masyarakat sering kali menemukan kambing hitam yang paling dekat. Ketika membicarakan masalah kemiskinan, stagnasi ekonomi, atau kesulitan dalam hidup, kita cenderung menyalahkan individu: "Kurang kerja keras," "boros," atau "tidak bisa mengatur uang." Narasi ini sudah begitu umum hingga terdengar seperti kebenaran mutlak. Seolah-olah semua orang miskin hanya perlu lebih rajin, lebih disiplin, dan lebih melek finansial agar masalahnya selesai.
Masyarakat sering kali menemukan kambing hitam yang paling dekat. Ketika membicarakan masalah kemiskinan, stagnasi ekonomi, atau kesulitan dalam hidup, kita cenderung menyalahkan individu: "Kurang kerja keras," "boros," atau "tidak bisa mengatur uang." Narasi ini sudah begitu umum hingga terdengar seperti kebenaran mutlak. Seolah-olah semua orang miskin hanya perlu lebih rajin, lebih disiplin, dan lebih melek finansial agar masalahnya selesai.
Padahal, realitasnya tidak sesederhana itu. Ya, tentu ada faktor individu yang berpengaruh: kurangnya literasi keuangan, perilaku konsumtif, atau tidak adanya perencanaan finansial jangka panjang. Tapi faktor-faktor tersebut hanya sebagian kecil dari cerita besar. Di balik perjuangan individu, ada sistem dan struktur ekonomi yang jauh lebih kuat dan sering kali menentukan seberapa jauh seseorang bisa naik kelas.
Banyak orang kelas menengah dan bawah di Indonesia bukan tidak berusaha. Mereka bekerja keras, bahkan kadang memiliki dua atau tiga pekerjaan sekaligus. Tapi tetap saja, hidup terasa seperti jalan di tempat. Penghasilan naik sedikit, biaya hidup naik lebih cepat. Gaji bertambah, tapi daya beli menurun. Di sinilah pentingnya kita menyadari bahwa bukan semata-mata "orangnya malas," melainkan sistem ekonominya memang tidak berpihak.
Inflasi dan Biaya Hidup yang Berlari Lebih Cepat dari Gaji
Bayangkan seseorang yang berlari sekuat tenaga di atas treadmill. Ia berkeringat, ngos-ngosan, tapi posisinya tidak bergerak maju. Itulah perumpamaan paling pas untuk menggambarkan kondisi ekonomi banyak pekerja di Indonesia hari ini. Setiap tahun, pemerintah mengumumkan kenaikan upah minimum. Secara angka, kabar itu terdengar positif. Tapi ketika dibandingkan dengan kenaikan harga kebutuhan pokok, hasilnya sering kali timpang. Harga beras, telur, minyak, kontrakan, transportasi, hingga biaya listrik dan air naik lebih cepat dari pertumbuhan upah. Kenaikan gaji 5% tidak berarti banyak ketika harga kebutuhan naik 10%. Artinya, meski nominal gaji bertambah, daya belinya justru turun. Uang yang dulu bisa cukup sampai akhir bulan, kini baru tanggal 20 sudah mulai menipis.
Bagi keluarga kelas menengah bawah, kondisi ini menciptakan mode hidup bertahan. Gaji habis untuk kebutuhan paling dasar: makan, sewa tempat tinggal, ongkos kerja, dan biaya pendidikan anak. Tidak ada ruang tersisa untuk tabungan, apalagi investasi. Akibatnya, impian naik kelas menjadi semakin jauh, bahkan terasa mustahil. Dan yang paling menyakitkan, inflasi ini tidak dirasakan secara merata. Yang paling terasa adalah inflasi bahan pokok sesuatu yang sangat berdampak pada kelompok berpenghasilan rendah. Bagi orang kaya, kenaikan harga beras seribu rupiah tidak berarti apa-apa. Tapi bagi keluarga dengan penghasilan pas-pasan, itu bisa mengurangi jatah lauk untuk anak.
Nilai Aset yang Terus Naik, Tapi Tidak Terjangkau
Masuk ke kekuatan ekonomi berikutnya: pertumbuhan nilai aset yang jauh lebih cepat dibanding kemampuan orang biasa untuk memilikinya. Fenomena ini bisa dilihat jelas di sektor properti. Harga rumah di kota-kota besar kini melonjak hingga dua atau tiga kali lipat dibanding sepuluh tahun lalu. Dulu, orang tua kita masih bisa membeli rumah di usia 30-an. Sekarang, banyak anak muda di usia yang sama bahkan belum sanggup menabung untuk uang muka. Harga properti naik 10% per tahun, sementara gaji mungkin hanya naik 45%.
Dalam kondisi ini, generasi baru seolah berlari mengejar sesuatu yang kecepatannya dua kali lipat lebih tinggi dari mereka. Dan sebelum sempat sampai, jaraknya sudah makin jauh. Sementara itu, mereka yang sudah lebih dulu memiliki aset tanah, rumah, atau saham tinggal duduk menikmati pertumbuhan nilainya. Tanpa harus menambah jam kerja, tanpa lembur, kekayaan mereka bertambah secara otomatis. Inilah salah satu sumber utama ketimpangan ekonomi: aset bekerja untuk orang kaya, sementara orang biasa harus terus bekerja untuk bisa hidup.
Sayangnya, sebagian besar masyarakat kelas menengah bawah belum punya akses ke aset produktif. Uang mereka banyak parkir di tabungan dengan bunga kecil, atau malah tersedot untuk konsumsi jangka pendek motor baru, gadget terbaru, atau cicilan rumah yang nilai bersihnya masih negatif karena utang. Akibatnya, yang tercipta adalah ilusi kemapanan. Secara tampilan, seseorang terlihat mapan: punya kendaraan, rumah KPR, atau gaya hidup modern. Tapi secara finansial, rapuh. Sebagian besar "kekayaannya" masih utang.
Konsumsi yang Didorong Utang: Jebakan Gaya Hidup Modern
Satu lagi kekuatan ekonomi yang diam-diam mempersempit ruang gerak masyarakat kelas menengah bawah adalah sistem konsumsi berbasis utang. Dulu, utang identik dengan bank atau kartu kredit. Sekarang, utang sudah menyusup ke dalam aplikasi di ponsel kita. Ada fitur "bayar nanti", "cicilan 0%", bahkan pesan makanan pun bisa dicicil. Semuanya dibuat semudah mungkin, seolah-olah utang adalah hal normal dan ringan. Awalnya mungkin kecil: Rp100.000 atau Rp200.000. Tapi kebiasaan itu lama-lama menumpuk. Setiap kali gajian, sebagian pendapatan sudah otomatis hilang untuk membayar cicilan bulan lalu.
Yang lebih menyedihkan, bagi banyak keluarga, utang ini bukan untuk foya-foya. Kadang hanya untuk menutup kebutuhan pokok belanja dapur, biaya sekolah, atau kebutuhan anak. Tapi tetap saja, sistemnya membuat mereka kehilangan kontrol. Di balik kemudahan itu ada bunga, biaya layanan, dan denda keterlambatan yang perlahan menggerogoti penghasilan. Sementara orang kaya menikmati bunga investasi, kelas pekerja justru menanggung bunga utang. Dua arah yang berlawanan tapi sama-sama majemuk satu menumbuhkan kekayaan, yang lain memperbesar beban.
Pajak dan Kebijakan yang Tidak Simetris
Kalau bicara soal kebijakan ekonomi, di atas kertas semuanya terlihat adil. Semua warga negara wajib bayar pajak sesuai aturan. Tapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Bagi pekerja bergaji tetap, pajak dipotong langsung dari gaji setiap bulan. Tidak ada ruang untuk menunda, tidak ada strategi untuk mengatur jumlah potongan. Gaji bersih yang diterima sudah hasil akhir setelah potongan pajak dan iuran. Sementara itu, kelompok yang punya usaha, investasi, atau aset besar punya banyak cara untuk mengatur beban pajaknya. Mereka bisa memanfaatkan insentif, potongan biaya operasional, bahkan pengaturan waktu pelaporan untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan semua legal dan sah.
Perbedaan akses informasi dan sumber daya ini menciptakan ketimpangan struktural. Orang yang hidup dari gaji membayar pajak lebih besar proporsinya dibanding mereka yang hidup dari modal. Belum lagi pajak konsumsi (PPN) yang dibebankan ke semua orang, tanpa memandang penghasilan. Hasilnya, beban pajak justru lebih berat bagi kelompok menengah bawah yang setiap rupiahnya digunakan untuk kebutuhan dasar. Sementara kelompok atas punya ruang manuver untuk menekan beban pajak dan mengalokasikan uang lebih banyak ke investasi baru.
Menyadari Akar Masalah: Bukan Malas, Tapi Terjebak Sistem
Semua kekuatan ekonomi ini inflasi yang melampaui upah, pertumbuhan aset yang timpang, konsumsi berbasis utang, dan kebijakan yang tidak simetris saling berkelindan membentuk realitas yang kita hadapi hari ini. Mereka menciptakan kondisi di mana banyak orang merasa sudah berlari sekuat tenaga, tapi tetap tidak maju. Dan ironisnya, masyarakat sering kali diajarkan untuk menyalahkan diri sendiri, bukan sistem yang menjerat. Padahal, memahami struktur yang lebih besar bukan berarti berhenti berusaha. Justru sebaliknya: kesadaran ini penting agar kita bisa berpikir lebih kritis dan realistis. Bahwa kerja keras saja tidak cukup kalau sistemnya tidak adil. Bahwa literasi finansial harus dibarengi dengan kesadaran struktural. Dan bahwa perubahan ekonomi sejati tidak akan terjadi hanya di level individu, tapi juga di level kebijakan dan struktur. Kita boleh bangga dengan kerja keras kita, tapi kita juga berhak marah pada sistem yang tidak memberi ruang yang sama bagi semua orang untuk maju. Karena kalau tidak, kita akan terus percaya bahwa kemiskinan adalah kesalahan pribadi padahal sering kali, ia adalah produk dari sistem yang memang didesain tidak setara.












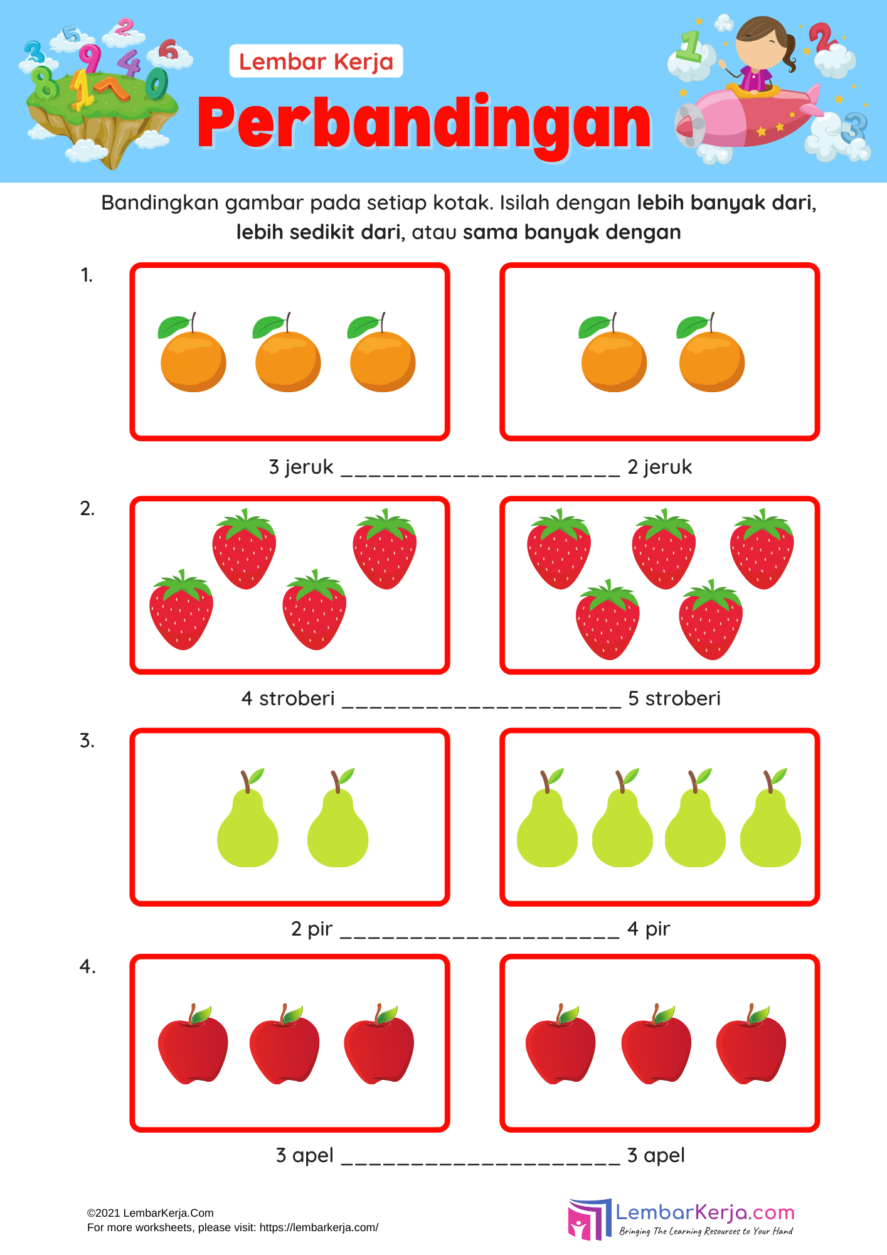

Komentar
Kirim Komentar